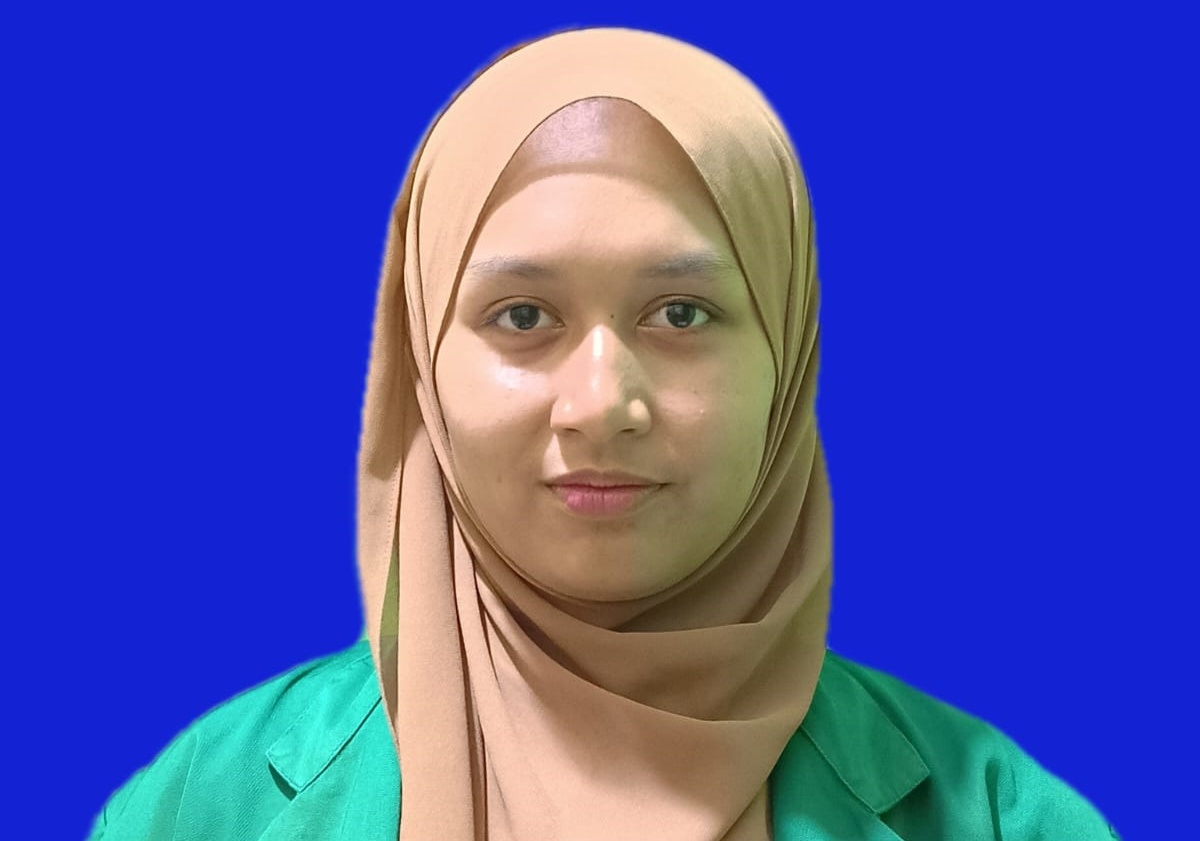Korupsi adalah musuh bersama yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah struktural yang merambah hampir semua lini: dari pemerintahan pusat, daerah, hingga ke sektor swasta. Kerugian negara yang ditimbulkan pun bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka, muncul satu pertanyaan krusial: dalam upaya melawan korupsi, mana yang lebih efektif—reformasi hukum atau penerapan hukuman mati?
Pertanyaan ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga sangat praktis. Di satu sisi, banyak yang mendorong perbaikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa hukuman mati dapat memberi efek jera yang maksimal bagi para koruptor. Namun, sebelum menentukan mana yang paling ampuh, mari kita bedah lebih dalam dua pendekatan ini.
Hukuman Mati: Menakutkan, tapi Apakah Efektif?
Gagasan menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya bukan hal baru. Beberapa negara seperti China, Iran, dan Vietnam telah lama menerapkan kebijakan ini. Dalam praktiknya, negara-negara tersebut memang menunjukkan penurunan kasus korupsi yang signifikan dalam beberapa periode tertentu. Efek jera seolah menjadi senjata utama dalam pendekatan ini.
Namun, apakah itu berarti hukuman mati benar-benar efektif? Jawabannya tidak sesederhana itu.
Pertama, korupsi bukanlah kejahatan yang terjadi secara spontan atau emosional, melainkan terencana. Koruptor biasanya telah menghitung risiko—dan dalam beberapa kasus, merasa aman karena kelemahan sistem hukum. Dalam konteks ini, ancaman hukuman mati bisa saja tidak relevan jika sistem peradilan yang menangani kasusnya masih penuh celah.
Kedua, penerapan hukuman mati membutuhkan sistem hukum yang benar-benar bersih dan akurat. Salah sedikit dalam proses hukum bisa berakibat fatal. Bayangkan jika seseorang dihukum mati padahal tidak bersalah? Di negara dengan sistem hukum yang masih rentan terhadap suap dan tekanan politik, ini adalah resiko besar yang tak bisa diabaikan.
Ketiga, dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Banyak organisasi internasional seperti Amnesty International menentang keras hukuman mati, apapun bentuk kejahatannya.
Reformasi Hukum: Membangun dari Akar
Reformasi hukum adalah pendekatan yang lebih mendasar dan sistematis. Fokusnya adalah memperbaiki sistem peradilan dari hulu ke hilir: penegakan hukum yang profesional, transparansi proses hukum, independensi lembaga peradilan, serta penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Melalui reformasi hukum, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Misalnya, dengan sistem pelaporan kekayaan pejabat negara yang transparan, sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital, serta perlindungan terhadap whistleblower.
Selain itu, reformasi hukum juga mencakup pendidikan hukum bagi masyarakat dan penanaman nilai-nilai integritas sejak dini. Perubahan budaya hukum adalah komponen penting agar masyarakat tidak permisif terhadap praktik-praktik koruptif.
Contoh nyata bisa kita lihat di negara-negara seperti Singapura dan Denmark. Mereka tidak menerapkan hukuman mati untuk korupsi, tetapi sukses menjadi negara dengan tingkat korupsi sangat rendah. Kuncinya terletak pada penegakan hukum yang konsisten, transparansi birokrasi, dan keterbukaan informasi publik.
Studi Kasus: Indonesia dan Tantangan Ganda
Indonesia sebenarnya telah melakukan banyak upaya reformasi hukum. Berdirinya KPK pada tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini telah berhasil mengungkap berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Namun, dalam perkembangannya, KPK pun menghadapi banyak tantangan, terutama dalam aspek independensi dan politik hukum yang berubah-ubah.
Di sisi lain, wacana hukuman mati bagi koruptor kembali menguat saat kasus-kasus besar mencuat, seperti korupsi bansos atau proyek infrastruktur. Sentimen publik yang geram membuat hukuman mati menjadi semacam pelampiasan emosional atas rasa ketidakadilan.
Padahal, tanpa pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum, hukuman seberat apapun tidak akan menyentuh akar masalah. Penyuapan dalam proses hukum, pemilihan hakim yang tidak transparan, hingga intervensi kekuasaan dalam proses penyidikan adalah masalah nyata yang sering membatalkan keadilan.
Efek Jera atau Efek Bersih?
Masyarakat cenderung menginginkan efek jera. Hukuman berat, termasuk hukuman mati, dianggap bisa membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Namun perlu diingat, efek jera hanya bekerja dalam sistem hukum yang konsisten dan dapat dipercaya. Jika tidak, maka hukuman berat justru berisiko disalahgunakan.
Reformasi hukum, walau butuh waktu dan proses panjang, memberi efek bersih— membersihkan sistem dari dalam, menciptakan keadilan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, efek bersih ini justru lebih kuat dibanding efek jera yang hanya sesaat.
Kesimpulan: Jalan Mana yang Harus Dipilih?
Memilih antara reformasi hukum dan hukuman mati bukan seperti memilih antara siang dan malam. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal efektivitas dalam konteks jangka pendek dan panjang.
Hukuman mati bisa jadi solusi ekstrem, tapi bukan solusi sistemik. Tanpa sistem hukum yang bersih, ancaman hukuman mati justru bisa menjadi alat politik, bukan keadilan.
Sebaliknya, reformasi hukum adalah investasi jangka panjang yang akan menciptakan sistem yang adil, bersih, dan berdaya cegah tinggi. Meskipun prosesnya panjang dan penuh tantangan, reformasi hukum memberi pondasi kuat untuk melawan korupsi secara menyeluruh.
Mungkin inilah saatnya kita bertanya ulang, bukan hanya “hukuman apa yang pantas untuk koruptor?”, tapi juga “sistem seperti apa yang bisa mencegah orang menjadi koruptor sejak awal?”
Korupsi tidak akan pernah hilang hanya dengan menakut-nakuti, tapi bisa dilawan dengan membangun sistem yang bersih, adil, dan tak bisa ditawar-tawar.
Penulis: Annisha Arrahmani Channya Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas